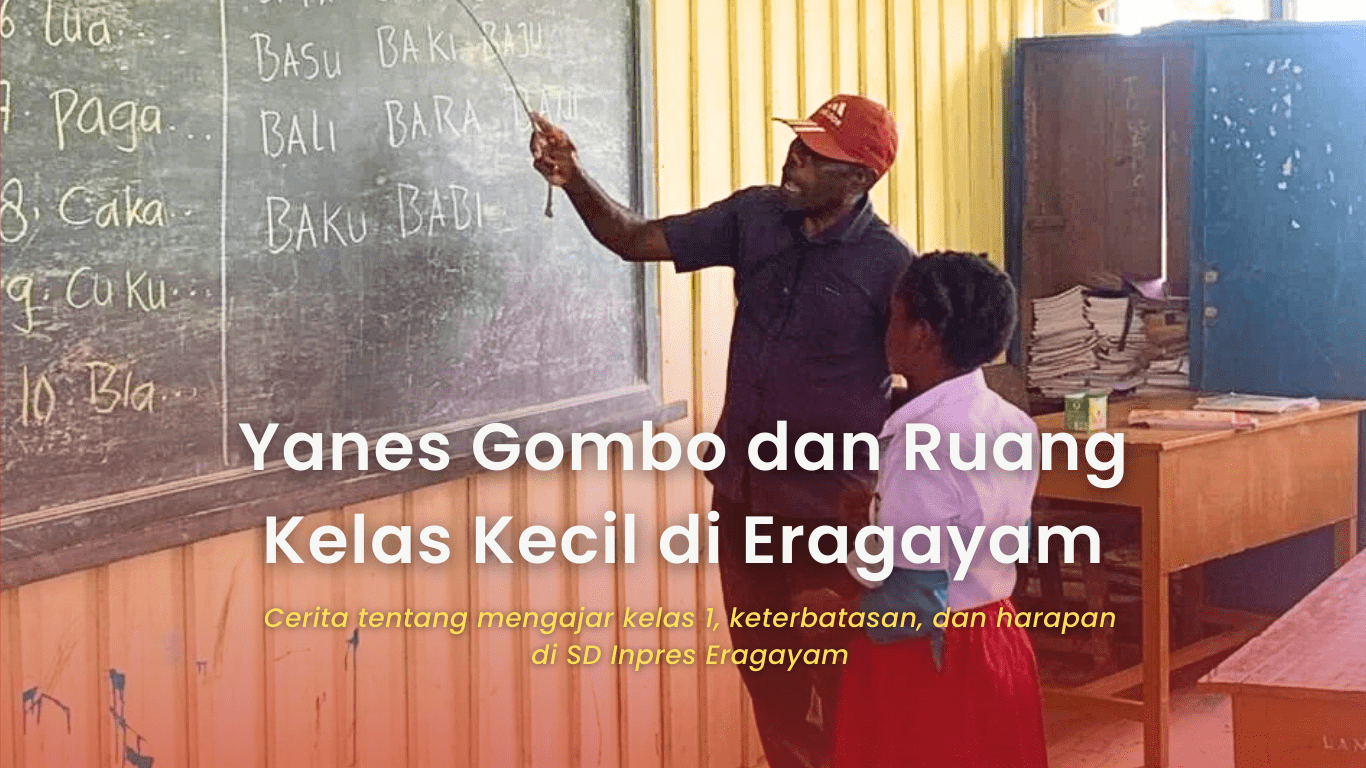Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, akhir September lalu menjadi pengalaman yang membekas bagi beberapa fasilitator pendidikan kami. Suara tembakan, kios-kios terbakar, massa berlarian, hingga orang-orang yang panik menyelamatkan diri semua terjadi begitu cepat.
Pagi itu, Kak Helena dan Kak Rosdiana, fasilitator YNS sedang berangkat menuju sekolah intervensi. Namun sebelum tiba, suara tembakan terdengar dari arah SMA Negeri 1 Elelim. “Kami masih di pertengahan jalan waktu itu, tiba-tiba tiga kali suara tembakan terdengar. Mama-mama dari pasar langsung berlarian ke arah kami,” kenang Rosdiana. Panik, mereka memutar motor dan mencari perlindungan di SD Pirip.
Di sekolah itu, kegiatan belajar masih berjalan. Tapi tak lama, seorang orang tua datang memperingatkan guru-guru agar segera memulangkan anak-anak. Situasi dianggap sudah tidak kondusif. “Tidak lama kemudian, massa turun ke desa. Dari jendela rumah di belakang sekolah, saya bisa lihat kios-kios terbakar, tembakan di mana-mana, dan teriakan massa yang mengancam pendatang,” ujar Helena.

*Sumber Foto: BBC News Indonesia
Dalam hitungan menit, desa Pirip menjadi salah satu pusat kericuhan. Guru-guru dan fasilitator terpaksa bersembunyi di rumah warga. Di tengah kepanikan itu, mereka harus menahan rasa takut saat terdengar teriakan massa di luar: “Panah mereka! Panah mereka!” Bahkan seorang remaja sempat mengancam dengan busur panah, sebelum akhirnya pemilik rumah melindungi dan menyuruh mereka bersembunyi di kamar dengan selimut menutupi tubuh.
Bagi Rosdiana, momen itu semakin sulit ketika ia terpisah dari tim fasilitator lain. Ia bersama beberapa guru SD Pirip harus berpindah-pindah, bahkan sempat melompati pagar setinggi dada orang dewasa sambil menenteng beberapa tas laptop milik teman-temannya. “Saat itu saya sadar, dalam kondisi seperti ini, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah diri kita sendiri dan doa. Saya hanya bisa berlari dan percaya Tuhan menolong,” katanya.
Di tengah ketegangan itu, ada dua hal yang membuat para fasilitator bisa bertahan. Pertama, sebelum turun lapangan fasilitator dibekali pelatihan menghadapi situasi darurat. Mereka dilatih untuk tetap tenang, mencari perlindungan yang aman, serta mengutamakan keselamatan anak dan guru. “Kalau tidak ada pelatihan itu, mungkin kami panik dan salah mengambil keputusan,” ujar Rosdiana.

Kedua, hubungan baik yang selama ini dijaga dengan masyarakat sekitar terbukti menjadi penyelamat. Warga lokal ikut melindungi dan menyembunyikan para fasilitator serta guru, bahkan mengarahkan mereka ke tempat aman. Kepercayaan dan kedekatan inilah yang membuat para fasilitator tidak merasa sendirian di tengah ancaman.
Menjelang malam, api semakin mendekati tempat persembunyian. Mereka harus berpindah menuju rumah Kepala Sekolah SMK Yapesli dengan berjalan dalam gelap gulita tanpa senter, agar tidak menarik perhatian massa. Hingga akhirnya, evakuasi baru bisa dilakukan menjelang tengah malam dengan truk, juga dalam keheningan tanpa suara.
Meski pengalaman ini meninggalkan trauma, Helena dan Rosdiana tidak kehilangan semangatnya. “Bagaimanapun yang terjadi, saya ingin terus bekerja untuk anak-anak Papua,” tutur Helena.
Cerita dari Yalimo ini mengingatkan kita bahwa perjuangan pendidikan di Papua bukan hanya soal jarak dan keterbatasan akses, tetapi juga tentang keberanian dan keteguhan hati orang-orang yang memilih untuk tetap ada di tengah masyarakat.